Oleh Tgk Abdullah Tsani*
Aceh Publish - Sudah 13 abad. Begitulah lama Islam menyinari tanah Aceh. Sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi, Aceh telah menjadi tempat pertama bagi masuknya Islam ke Nusantara. Mengingat perjalanan panjangnya, seharusnya Aceh sudah matang dalam menjalankan syariat Islam. Bahkan, kita sudah memasuki milenium kedua Islam di Aceh. Tapi, apa yang terjadi sekarang? Kita masih sibuk mengundang dai-dai luar. Untuk apa?
Bukan tidak menghargai ilmu yang dibawa oleh ulama dari luar, namun kita perlu bertanya, “Mengapa kita masih tergantung pada mereka?” Sudah lebih dari 13 abad kita menggeluti Islam, dan selama itu pula sudah banyak ulama lokal yang lahir. Ulama-ulama ini bukan orang baru dalam dakwah. Mereka bukan orang yang belajar Islam secara instan atau sekadar meniru apa yang dipelajari dari luar. Mereka tahu persis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. Mereka memahami konteks lokal—sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh dai luar dalam sekali ceramah.
Namun, apa yang terjadi? Mengapa kita masih merasa perlu mengundang dai luar, seolah-olah ulama Aceh tidak cukup baik? Mungkin kita masih tergoda oleh cahaya yang datang dari luar. Cahaya yang sesaat, yang tidak lebih dari kilau rembulan yang indah namun tidak memberikan kehangatan. Pepatah mengatakan, “Hidupkan cahaya sendiri, jangan terlalu percaya pada cahaya rembulan, hanya sesaat.” Rembulan memang menawan, tapi ia tidak memberi kehidupan. Cahaya rembulan hanya ada sesaat, terkadang terhalang awan, dan sering kali tak bisa diandalkan. Sebaliknya, cahaya matahari bersinar lebih kuat, memberi kehidupan, dan selalu ada.
Aceh sudah cukup lama berada dalam cahaya Islam yang terang. Mengapa kita masih meraba-raba, mencari-cari cahaya luar? Sudah saatnya kita hidup dengan cahaya yang kita miliki sendiri. Kita telah lama berdiri di bawah naungan Islam. Mengapa masih terperangkap dalam bayang-bayang ulama luar?
Syariat Islam di Aceh sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000. Itu bukan sekadar formalitas. Sudah 24 tahun, syariat Islam diterapkan dengan baik di Aceh. Namun, meskipun sudah ada landasan yang jelas dan kuat, kita tetap merasa kurang. Ada yang merasa, tanpa ulama luar, kita tidak cukup baik. Kenapa harus begitu? Bukankah kita sudah cukup dewasa? Mengapa harus terus mengundang mereka yang datang sesaat, padahal kita sudah memiliki ulama yang memahami Aceh jauh lebih dalam?
Saya bukan menentang ulama luar. Mereka tentu memiliki ilmu yang luar biasa, dan ilmu mereka sangat berharga. Namun, kita juga harus memikirkan mengapa kita terus-menerus merasa bahwa ilmu luar selalu lebih tinggi. Bukankah kita juga punya kekayaan intelektual yang tak kalah hebatnya? Ulama Aceh bukanlah orang yang kurang pengetahuan. Mereka sudah lama berjuang di tanah ini. Mereka tahu persis bagaimana Islam berkembang di Aceh, dengan segala dinamikanya yang sangat khas. Mereka memahami adat-istiadat Aceh, cara hidup masyarakatnya, dan bagaimana Islam bisa diterima dengan baik.
Jadi, saya bertanya lagi: untuk apa kita mengundang mereka? Mengapa kita merasa bahwa ulama luar lebih mampu mengajarkan kita apa yang sudah kita ketahui? Apakah kita sudah lupa bahwa Aceh memiliki potensi yang luar biasa?
Jika kita bisa menjadi penterjemah untuk dai luar yang datang ke Aceh, mengapa kita tidak bisa mempromosikan ulama Aceh ke luar negeri agar diundang ke masjid, halaqah, atau kampus-kampus di dunia? Bukankah mereka juga layak berbicara di sana? Bukankah mereka punya kredibilitas yang tak kalah dengan ulama luar? Mengapa kita tak pernah mempromosikan mereka seperti kita mempromosikan ulama dari luar yang datang ke sini?
Coba kita pikirkan sejenak. Jika kita terus-menerus bergantung pada ulama luar, kita akan terjebak dalam ketergantungan itu. Kita tidak akan pernah bisa berdiri dengan kaki kita sendiri.
Sebaliknya, jika kita mulai memberi ruang lebih kepada ulama Aceh, jika kita mempromosikan mereka di luar negeri, kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah cukup dewasa. Kita bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Kita tidak butuh lagi cahaya rembulan yang datang sementara; kita sudah punya matahari yang terus bersinar.
Ada saatnya kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Aceh sudah cukup matang. Sudah saatnya kita berhenti terjebak dalam bayang-bayang ulama luar dan mulai mengangkat ulama Aceh sebagai pemimpin. Jangan lagi biarkan ulama lokal terpinggirkan. Mereka sudah cukup lama berkecimpung di dunia dakwah. Mereka sudah membuktikan diri sebagai pelayan agama yang memahami dengan baik kehidupan masyarakat Aceh.
Jika kita terus-menerus menoleh ke luar, kita akan kehilangan potensi besar yang ada di depan mata. Aceh memiliki banyak ulama yang kompeten. Mereka sudah terbukti dan teruji dalam menjalankan syariat Islam sesuai dengan konteks lokal yang ada. Jadi, mengapa tidak memberi mereka kesempatan untuk bersinar di luar? Kenapa kita harus mengundang orang lain untuk berbicara tentang kita, sementara kita tidak pernah memberikan kesempatan pada diri kita sendiri?
Cahaya kita sudah cukup terang. Islam di Aceh sudah cukup kuat untuk berkembang, bahkan di tingkat internasional. Cobalah kampanyekan ulama Aceh di luar sana. Bawa mereka ke halaqah ilmu di Arab, di kampus-kampus dunia. Jadilah penterjemah mereka. Mengapa tidak? Ulama luar yang datang ke sini sudah diberi tempat, kini saatnya giliran ulama Aceh yang diberi kesempatan di luar.
Sudah saatnya kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sudah saatnya kita memimpin dakwah, bukan sekadar menjadi penonton. Kita memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kita punya kapasitas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Aceh bukan hanya label Serambi Mekkah. Aceh adalah bukti hidup bagaimana Islam bisa berkembang dengan kekuatan lokal, dengan pemahaman yang sangat mendalam terhadap budaya, adat, dan masyarakatnya.
Mari berhenti bergantung pada cahaya luar yang sesaat. Mari mulai hidup dengan cahaya kita sendiri. Kita sudah cukup lama dalam cahaya Islam. Sekarang saatnya untuk membuktikan kepada dunia bahwa Aceh bisa menjadi pemimpin dalam dakwah, dengan ilmu dan kearifan lokal yang kita miliki.
*Penulis adalah pecinta ilmu ulama Aceh dan sekarang tinggal di Kota Nasaf, Uzbekistan, Asia Tengah
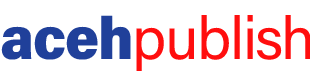
 Komentar
Komentar